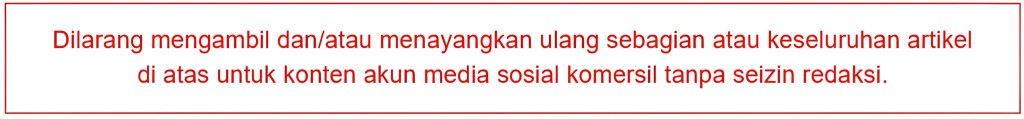Petani Dalam “Perang Dagang” EUDR
Ekonomi & Bisnis
September 26, 2025
Jon Afrizal/Kota Jambi

Petani karet di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. (credits: Yayasan Setara)
SEBANYAK sembilan petani perempuan Indonesia dibawa oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke tiga kota di Eropa, pada tanggal 13 hingga 20 September 2025 lalu. Kesembilannya berkunjung ke Belgia, Inggris dan Italia, dan bertemu banyak pihak.
Kesembilan petani ini berasal dari Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat, Sulawesi dan Papua. Mereka, oleh Kemenlu, dimintakan untuk membawa echo dari para petani karet, kopi, kakao dan sawit di Indonesia. Juga, dengan tujuan agar petani memahami skema European Deforestation Regulation (EUDR).
Dan, ketika petani juga terpaksa harus ikut memahami skema perdagangan antar negara, sungguh, tugas petani bertambah berat. EUDR, adalah regulasi perdagangan antar negara, dimana pemerintah dan negara memiliki peran utama.
“Ketika petani harus memahami apa itu peta polygon, titik koordinat kebun dan melakukan pengolahan data digital, tentu saja petani akan kewalahan,” kata Kusniati petani karet dari Kabupaten Tebo, yang ikut serta berkunjung ke Eropa.
Seharusnya, katanya, petani mendapat dukungan teknis, bimbingan dan dukungan finansial, baik itu dari pemerintah ataupun dari pihak lainnya.
Pengetahuan mereka, katanya, sejauh ini baru sampai ke tahapan standard Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) danRoundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) saja. Itupun, sejujurnya, para petani harus lebih banyak berbenah dalam menerapkan good agriculture practice.
Dan, ketika mereka harus mengikuti standard EUDR yang jauh berbeda dari ISPO dan RSPO, maka, pemerintah dan negara sudah seharusnya memposisikan diri untuk melindungi petani.
Namun di era globalisasi dan keterbukaan informasi ini, maka, petani harus memahami regulasi, dan bahkan menindaklanjuti kebijakan pasar Uni Eropa yang anti-deforestasi.
EUDR adalah regulasi anti-deforestasi yang diterapkan oleh pasar Uni Eropa, sebagai pembeli, kepada para penjual yang berada di wilayah di luar Eropa. Aturan ini telah berkali-kali ditunda pelaksanaannya.

Skema EUDR. (credits: Tracextech)
Mengutip laman Discourse on Development pada Selasa (23/09), aturan ini kembali ditunda penerapannya setidaknya selama satu tahun ke depan. Penundaan ini dipicu oleh keberatan dari mitra dagang utama, seperti Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat, terkait manajemen data dalam sistem Teknologi Informasi (TI).
Untuk Indonesia, aturan ini akan berdampak pada rantai pasok tujuh komoditas. Yakni; kayu, kakao, karet, kopi, kedelai, sawit dan daging sapi.
“Tidak ada kemungkinan bahwa petani yang telah bersertifikat akan dapat lansung dinyatakan lolos untuk menjual hasil panennya,” kata Cici Tian Sari, anggota Koperasi Agro Tani Lestari (KATL) dari Kabupaten Sarolangun.
Maka, penjelasan panjang tentang apa itu “rantai pasok” akan segera memasuki desa-desa sebagai sentra pertanian. Petani akan semakin sibuk mendengar “ceramah-ceramah” tentang perdagangan antar negara yang dibungkus dengan tema: bahaya deforestasi dan perubahan iklim dan seterusnya dan seterusnya.
Sementara, yang seharusnya dilakukan petani, sejak dari dulu, adalah: bertani.
Sehingga, yang diperlukan petani adalah ilmu pertanian, dan bukan ilmu perdagangan. Karena toh, mereka adalah petani dan bukan pedagang, apalagi eksportir.
Padahal, EUDR seharusnya menyasar para pelaku pasar, dan bukan petani. Ketika petani, diharuskan ikut serta dalam “perang dagang”, ini tentu bukanlah fairness.
Terdapat persyaratan due diligence yang diterapkan EUDR, yakni: geolokasi, legalitas kebun dan legalitas petani. Tentunya adalah tantangan tersendiri bagi eksportir, yang kemudian “meneruskan beban” ini kepada petani swadaya sebagai pemasok mereka.
Persyaratan yang tidak mudah bagi petani Indonesia pada umumnya, dengan keterbatasan secara pengetahuan, teknologi dan kemampuan teknis untuk pengolahan data digital.
Padahal, mengutip BPS, sebanyak 72,78 presen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2024. Namun, tidak diketahui secara pasti tentang persentasi penduduk yang telah “melek” internet. Sebab, “mengakses” dan “melek” adalah berbeda, dalam penerapannya.
“Kebijakan ini seharusnya diterapkan dengan kehati-hatian, dengan memperhatikan fleksibilitas ataupun pendekatan bertahap bagi petani swadaya. Jika tidak, maka kebijakan ini berpotensi menyingkirkan petani swadaya dari rantai pasok global ke pasar Uni Eropa,” kata Umi Syamsiatun, Direktur Perkumpulan Alam Hijau.
Komoditas sawit, mengutip Kemenkeu, menjadi satu motor penggerak pada produk domestik bruto (PDB) pada sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa PDB pada sektor pertanian dan perkebunan tumbuh positif sebesar 1,69 persen, pada Triwulan III-2024. Pun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 tercatat sebesar 4,95 persen.
Industri sawit adalah satu penyumbang terbesar untuk ekspor nonmigas Indonesia. Menurut data Kementerian Perdagangan, terhitung hingga September 2024 ekspor nonmigas sebesar USD 181,14 milyar, dan untuk ekspor lemak dan minyak nabati mencapai USD 14,43 Milyar termasuk didalamnya minyak sawit.
Masih menurut data BPS, pada 2023, Provinsi Jambi memiliki kebun karet seluas 664.814 hektare dengan total produksi karet sebanyak 326.407 ton per tahun, dan, perkebunan sawit seluas 1.099.191 hektare dengan produksi sebanyak 2,23 juta ton per tahun, pada tahun 2022.

Petani sawit di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. (credits: Jon Afrizal/amira.co.id)
Kedua komoditas ini telah mencapai pasar Uni Eropa untuk berbagai sektor industri.
Luas perkebunan sawit di Indonesia, mengutip Climate Diplomacy, sejak tahun 1985 hingga 2014, bertambah dari 600.000 hektare menjadi 11,5 juta hektare.
Perlawanan dunia internasional terhadap industri sawit Indonesia pun telah terjadi. Pada tahun 2011, misalnya, aksi protes dilakukan di kantor Unilever di London, Inggris. Unilever adalah konsumen besar minyak sawit Indonesia untuk produk kosmetik.
Pun, Unilever dan “kepentingan-kepentingan yang lain” juga telah mendirikan RSPO. Dengan tujuan utama untuk memediasi pihak-pihak yang kontra terhadap industri sawit.
Bahwa, industri sawit harus bebas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pro lingkungan yang baik, dan berkelanjutan. Kata “berkelanjutan”, dapat diterjemahkan sebagai: masih dapat digunakan untuk kepentingan bisnis industri untuk jangka panjang.
Maka, adalah menjadi wajar jika petani meminta perlindungan dari pemerintah dan negara. Dan, tentu saja, sejauh mana pemerintah dan negara berperan dan ambil bagian dalam mencerdaskan petani di sektor digitalisasi.
Pun juga, memberi kepastian, bahwa pabrik, yang adalah perpanjangantangan eksportir di tingkat lokal, akan tetap membeli hasil panenan petani.
Jika tidak, maka harga panenan akan menjadi permainan pasar, dan, yang utama, tengkulak, ijon, makelar dan Bank Plecit akan sesegera mungkin mencekik petani.*